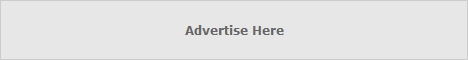==========================================================
Postingan pertama di awal tahun... Entah kenapa, ane merasa lucu sendiri sama kepolosannya Yui... Oiya, Namahage (生剥) adalah orang yang memakai kostum iblis guna menakut-nakuti anak-anak yang punya kelakuan buruk... Kalau begitu, saatnya membuat kue...Selamat Menikmati...
==========================================================Bab 3 - Berulang Kali, Yui Yuigahama Bersikap Gelisah
Bagian 5
Ruang PKK kini sudah dilputi oleh aroma vanili. Yukinoshita membuka lemari pendingin, seakan ia sudah tahu apa yang harus dilakukannya, lalu mengambil beberapa liter susu juga telur. Ia mengeluarkan timbangan dan sebuah mangkuk besar, kemudian menyiapkan beberapa butir telur, serta menggunakan bermacam peralatan memasak yang belum begitu kukenal.
Entah bagaimana, tampaknya manusia super sempurna ini juga sungguh hebat dalam hal memasak.
Setelah selesai dengan persiapan cepatnya tadi, ia kenakan celemeknya, seolah ingin menunjukkan kalau saat ini adalah waktunya memasak. Yuigahama pun ikut mengenakannya, namun sepertinya sudah kelihatan kalau ia belum pernah sekalipun mengenakan celemek; ia mengikat talinya dengan sembrono, sampai-sampai jadi kusut.
"Ikatan tali celemekmu kusut. Apa kau sungguh tak tahu caranya mengikat celemek?"
"Maaf. Terima kasih... eh, apa?! Kalau cuma mengikatnya saja, aku bisa, kok!"
"Kalau begitu, tolong ikat celemeknya dengan benar. Jika tidak, nanti kau bisa berakhir seperti anak itu – yang tak bisa kembali lagi ke titik balik hidupnya."
"Jangan menggunakanku sebagai contoh negatif. Memangnya aku ini Namahage?"
"Padahal ini pertama kalinya kau bisa tampak berguna bagi orang lain, harusnya kau sedikit senang... oh, tapi jangan cemas; meski kau membandingkan dirimu dengan Namahage, aku takkan mau macam-macam dengan kulit kepalamu, jadi tenang saja."
"Siapa juga yang cemas soal... hei, hentikan. Jangan pandang rambutku dengan senyum mencurigakan itu." Dengan maksud menghindar dari senyumnya – sebuah ekspresi yang biasanya tak pernah ia tunjukkan – kulindungi rambut ini dengan tanganku.
Kudengar tawa cekikik dari Yuigahama. Dan sudah ditebak, ia masih berusaha mengikat celemeknya sembari menyaksikan perdebatanku dengan Yukinoshita dari kejauhan.
"Jadi kau masih belum mengikatnya? Atau jangan-jangan kau memang tak bisa? ...ya ampun, ayo sini. Kubantu kau mengikatnya." Yukinoshita tampak frustasi, sekilas memberi isyarat pada Yuigahama.
"...ah, enggak apa-apa, kok." Gumam Yuigahama, menampakkan sedikit keraguan, dan bolak-balik melihat ke arahku dan ke arah Yukinoshita. Ia tampak seperti anak kecil yang sedang tersesat dan gelisah.
"Cepat sini." Nada bicara Yukinoshita yang dingin seakan menyingkirkan keraguan Yuigahama. Aku tak tahu apakah ia sedang marah atau tidak, yang pasti ia terlihat sedikit menakutkan.
"Ma-ma-ma-maaf!" Jawab Yuigahama dengan suara terpekik, lalu berjalan mendekat pada Yukinoshita. Memangnya ia anak anjing, apa?
Yukinoshita lalu bergerak ke belakang Yuigahama dan segera mengikat ulang tali celemek perempuan itu.
"Yukinoshita... rasanya kau jadi seperti kakakku saja, ya?"
"Yang jelas adikku takkan jadi separah dirimu." Yukinoshita mendesah dan tampak tak senang, namun entah kenapa, aku sebenarnya setuju dengan pemikiran Yuigahama.
Kalau melihat Yukinoshita yang dewasa bersanding dengan Yuigahama yang kekanak-kanakan, rasanya memang seperti sedang melihat pasangan kakak-beradik. Kalau dilihat lagi, memang terasa ada semacam jalinan kekeluargaan di antara mereka.
Di sisi lain, jika kebanyakan pria setengah baya menganggap bahwa perempuan akan tampak bagus bila mengenakan celemek tanpa memakai apa-apa di baliknya, justru menurutku akan terlihat sangat bagus jika ada seragam sekolah di balik celemek tersebut.
Saat membayangkannya, hatiku terasa begitu hangat dan tanpa sadar aku menyengir sendiri.
"He-hei, Hikki..."
"A-apa?" Suaraku terbata. Sial. Mungkin tampang di wajahku sempat terlihat menjijikkan tadi. Dan tanpa sengaja, jawaban gugupku malah menambah betapa jijiknya hal tersebut.
"Ba-bagaimana pendapatmu terhadap perempuan yang pandai memasak?"
"Bukannya aku tidak suka, sih. Bukan pula seolah para lelaki menganggap itu hal menarik."
"Be-begitu, toh..." Setelah mendengarnya, Yuigahama tersenyum lega. "Baiklah! Kita mulai sekarang!" Ia gulung lengan bajunya, memecahkan telur dan mulai mengocoknya. Lalu ditambahkannya tepung terigu, kemudian gula, mentega dan sedikit perisa, termasuk aroma vanili di dalamnya.
Meski aku bukan orang yang ahli dalam seni memasak, tapi bisa kulihat dengan jelas kalau kemampuan Yuigahama masih jauh dari normal. Aku yakin, bagi dirinya, membuat kue kering adalah hal yang berada di luar jangkauan. Padahal itu hal yang sangat sederhana, jadi bukan hal sulit untuk mengetahui seberapa jauh kompetensi dirinya dari standar normal. Kemampuan Yuigahama yang sebenarnya, tanpa ditutup-tutupi, telah terpampang jelas.
Yang pertama, kocokan telur. Masih ada cangkang yang ikut tercampur di dalamnya. Yang kedua, perisanya masih menggumpal. Yang ketiga, menteganya masih keras. Bisa ditebak, ia keliru mengganti tepung dengan garam, dan berlebihan menuang susu beserta aroma vanilinya hingga tumpah dari mangkuk.
Ketika sekilas pandanganku tertuju ke Yukinoshita, bisa kulihat wajahnya yang pucat sembari menaruh tangan di dahinya. Bahkan untuk juru masak payah sepertiku saja, sampai merinding. Apalagi Yukinoshita yang memang hebat dalam memasak, hal ini pasti sebuah aib besar.
"Sekarang kita perlu..." Yuigahama terhenti dan mengambil bubuk kopi.
"Kopi? Kukira itu untuk diminum, atau mungkin lebih mudah dicerna kalau dijadikan makanan, kali ya? Ide yang hebat."
"Eh? Bukan begitu. Justru ini bahan rahasianya. Anak lelaki enggak suka makanan manis, 'kan?" Wajah Yuigahama memerah sembari melanjutkan perkerjaannya. Dengan pandangan terfokus pada tangannya, adonan hitam segera terbentuk di tengah-tengah mangkuknya.
"Pastinya itu tak lagi jadi bahan rahasia."
"Waduh!? Ih. Biar nanti kutambahkan tepung saja supaya jadi lebih bagus." Nyatanya, ia cuma mengganti adonan hitam itu menjadi adonan yang lebih putih. Kemudian, gelombang besar dari kocokan telur mulai menyapu adonan tersebut, yang seakan menggambarkan kejinya neraka.
Biar kusimpulkan. Kemampuan memasak Yuigahama memang payah. Ini bukan tentang masalah mampu atau tidaknya – untuk kemampuan dasar saja ia tak punya. Sikap plinplannya di luar kewajaran, bahkan untuk melakukan hal yang mudah saja, ia gagal. Ia adalah orang yang tak ingin kujadikan partner saat tugas di laboratorium. Yang ada, ia cukup plinplan untuk membuat dirinya sendiri terbunuh.
Akhirnya benda itu pun selesai dipanggang, dan keluarlah kue panas yang terlihat gosong. Dari baunya saja bisa kutebak kalau rasanya pahit.
"Ko-kok bisa?" Yuigahama terpaku ngeri saat melihat sebuah aib di hadapannya.
"Aku sungguh tak mengerti... bagaimana mungkin ada kesalahan yang bisa terjadi secara berturut-turut...?" Gumam Yukinoshita. Kurasa ia berkata pelan begitu agar tak didengar Yuigahama. Meski begitu, ia tadi terlihat keceplosan karena geregetan.
Yuigahama mengambil aib itu dan meletakkannya di atas piring. "Mungkin kelihatannya saja begini, tapi... mana kita tahu sebelum mencicipinya!"
"Kau benar. Di sini kita punya orang yang bertugas untuk itu."
Aku tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Yukinoshita. Benda aneh ini kausuruh aku... kalau yang begini, namanya pengujian racun."
"Kok racun, sih?! ...racun ...ya, mungkin saja ini memang beracun?" Dibandingkan sangkalan yang dipaksakannya di awal, Yuigahama kini malah tampak cemas sambil memiringkan kepalanya, seakan ingin bertanya, Bagaimana ini?
Hal tersebut sudah tak perlu dijawab lagi. Kupalingkan wajahku dari ekspresi Yuigahama yang seperti anak anjing itu dan coba menarik perhatian Yukinoshita.
"Hei, apa ini benar-benar harus kumakan? Ini sangat mirip dengan batu arang yang dijual di Joyful Honda."
"Karena kami tak memakai bahan-bahan yang tak layak konsumsi, mestinya kau akan baik-baik saja. Setidaknya begitu. Dan..." Yukinoshita terhenti sejenak, lalu mulai berbisik. "...aku juga akan memakannya, jadi kau tak perlu risau."
"Serius? Jangan-jangan kau ini memang orang baik, ya? Atau jangan-jangan kau memang suka padaku?"
"...setelah kupikir lagi, lebih baik kau makan semuanya dan mati sendiri saja sana."
"Maaf. Tadi aku sempat kaget, makanya aku jadi mengoceh tak jelas." Semua gara-gara kue kering ini... meski patut dipertanyakan, apakah aib yang ada di hadapan kami ini masih bisa disebut kue kering.
"Aku memintamu untuk mencicipinya, bukan justru mempersoalkannya. Terlebih, aku sudah terlanjur menyetujui permintaan Yuigahama. Setidaknya aku harus bertanggung jawab." Yukinoshita menarik piring itu ke sisinya. "Jika tak bisa menemukan akar permasalahannya, situasi seperti ini takkan berakhir. Walau itu tak bisa dianggap sebagai harga yang dibutuhkan untuk sebuah rasa ingin tahu."
Yukinoshita memandangku setelah mengambil satu dari aib berwarna hitam itu – yang mungkin akan salah dikira batu bara. Matanya tampak sedikit berkaca-kaca. "Kita takkan mati, 'kan?"
"Justru itu yang mau kutanyakan..." Kupandangi Yuigahama, yang juga sedang memandang kami, yang seolah juga ingin ikut bergabung.
...bagus. Alangkah baiknya jika ia saja yang memakan semuanya. Ia pun harus mengerti penderitaan orang lain.
Entah bagaimana, tampaknya manusia super sempurna ini juga sungguh hebat dalam hal memasak.
Setelah selesai dengan persiapan cepatnya tadi, ia kenakan celemeknya, seolah ingin menunjukkan kalau saat ini adalah waktunya memasak. Yuigahama pun ikut mengenakannya, namun sepertinya sudah kelihatan kalau ia belum pernah sekalipun mengenakan celemek; ia mengikat talinya dengan sembrono, sampai-sampai jadi kusut.
"Ikatan tali celemekmu kusut. Apa kau sungguh tak tahu caranya mengikat celemek?"
"Maaf. Terima kasih... eh, apa?! Kalau cuma mengikatnya saja, aku bisa, kok!"
"Kalau begitu, tolong ikat celemeknya dengan benar. Jika tidak, nanti kau bisa berakhir seperti anak itu – yang tak bisa kembali lagi ke titik balik hidupnya."
"Jangan menggunakanku sebagai contoh negatif. Memangnya aku ini Namahage?"
"Padahal ini pertama kalinya kau bisa tampak berguna bagi orang lain, harusnya kau sedikit senang... oh, tapi jangan cemas; meski kau membandingkan dirimu dengan Namahage, aku takkan mau macam-macam dengan kulit kepalamu, jadi tenang saja."
"Siapa juga yang cemas soal... hei, hentikan. Jangan pandang rambutku dengan senyum mencurigakan itu." Dengan maksud menghindar dari senyumnya – sebuah ekspresi yang biasanya tak pernah ia tunjukkan – kulindungi rambut ini dengan tanganku.
Kudengar tawa cekikik dari Yuigahama. Dan sudah ditebak, ia masih berusaha mengikat celemeknya sembari menyaksikan perdebatanku dengan Yukinoshita dari kejauhan.
"Jadi kau masih belum mengikatnya? Atau jangan-jangan kau memang tak bisa? ...ya ampun, ayo sini. Kubantu kau mengikatnya." Yukinoshita tampak frustasi, sekilas memberi isyarat pada Yuigahama.
"...ah, enggak apa-apa, kok." Gumam Yuigahama, menampakkan sedikit keraguan, dan bolak-balik melihat ke arahku dan ke arah Yukinoshita. Ia tampak seperti anak kecil yang sedang tersesat dan gelisah.
"Cepat sini." Nada bicara Yukinoshita yang dingin seakan menyingkirkan keraguan Yuigahama. Aku tak tahu apakah ia sedang marah atau tidak, yang pasti ia terlihat sedikit menakutkan.
"Ma-ma-ma-maaf!" Jawab Yuigahama dengan suara terpekik, lalu berjalan mendekat pada Yukinoshita. Memangnya ia anak anjing, apa?
Yukinoshita lalu bergerak ke belakang Yuigahama dan segera mengikat ulang tali celemek perempuan itu.
"Yukinoshita... rasanya kau jadi seperti kakakku saja, ya?"
"Yang jelas adikku takkan jadi separah dirimu." Yukinoshita mendesah dan tampak tak senang, namun entah kenapa, aku sebenarnya setuju dengan pemikiran Yuigahama.
Kalau melihat Yukinoshita yang dewasa bersanding dengan Yuigahama yang kekanak-kanakan, rasanya memang seperti sedang melihat pasangan kakak-beradik. Kalau dilihat lagi, memang terasa ada semacam jalinan kekeluargaan di antara mereka.
Di sisi lain, jika kebanyakan pria setengah baya menganggap bahwa perempuan akan tampak bagus bila mengenakan celemek tanpa memakai apa-apa di baliknya, justru menurutku akan terlihat sangat bagus jika ada seragam sekolah di balik celemek tersebut.
Saat membayangkannya, hatiku terasa begitu hangat dan tanpa sadar aku menyengir sendiri.
"He-hei, Hikki..."
"A-apa?" Suaraku terbata. Sial. Mungkin tampang di wajahku sempat terlihat menjijikkan tadi. Dan tanpa sengaja, jawaban gugupku malah menambah betapa jijiknya hal tersebut.
"Ba-bagaimana pendapatmu terhadap perempuan yang pandai memasak?"
"Bukannya aku tidak suka, sih. Bukan pula seolah para lelaki menganggap itu hal menarik."
"Be-begitu, toh..." Setelah mendengarnya, Yuigahama tersenyum lega. "Baiklah! Kita mulai sekarang!" Ia gulung lengan bajunya, memecahkan telur dan mulai mengocoknya. Lalu ditambahkannya tepung terigu, kemudian gula, mentega dan sedikit perisa, termasuk aroma vanili di dalamnya.
Meski aku bukan orang yang ahli dalam seni memasak, tapi bisa kulihat dengan jelas kalau kemampuan Yuigahama masih jauh dari normal. Aku yakin, bagi dirinya, membuat kue kering adalah hal yang berada di luar jangkauan. Padahal itu hal yang sangat sederhana, jadi bukan hal sulit untuk mengetahui seberapa jauh kompetensi dirinya dari standar normal. Kemampuan Yuigahama yang sebenarnya, tanpa ditutup-tutupi, telah terpampang jelas.
Yang pertama, kocokan telur. Masih ada cangkang yang ikut tercampur di dalamnya. Yang kedua, perisanya masih menggumpal. Yang ketiga, menteganya masih keras. Bisa ditebak, ia keliru mengganti tepung dengan garam, dan berlebihan menuang susu beserta aroma vanilinya hingga tumpah dari mangkuk.
Ketika sekilas pandanganku tertuju ke Yukinoshita, bisa kulihat wajahnya yang pucat sembari menaruh tangan di dahinya. Bahkan untuk juru masak payah sepertiku saja, sampai merinding. Apalagi Yukinoshita yang memang hebat dalam memasak, hal ini pasti sebuah aib besar.
"Sekarang kita perlu..." Yuigahama terhenti dan mengambil bubuk kopi.
"Kopi? Kukira itu untuk diminum, atau mungkin lebih mudah dicerna kalau dijadikan makanan, kali ya? Ide yang hebat."
"Eh? Bukan begitu. Justru ini bahan rahasianya. Anak lelaki enggak suka makanan manis, 'kan?" Wajah Yuigahama memerah sembari melanjutkan perkerjaannya. Dengan pandangan terfokus pada tangannya, adonan hitam segera terbentuk di tengah-tengah mangkuknya.
"Pastinya itu tak lagi jadi bahan rahasia."
"Waduh!? Ih. Biar nanti kutambahkan tepung saja supaya jadi lebih bagus." Nyatanya, ia cuma mengganti adonan hitam itu menjadi adonan yang lebih putih. Kemudian, gelombang besar dari kocokan telur mulai menyapu adonan tersebut, yang seakan menggambarkan kejinya neraka.
Biar kusimpulkan. Kemampuan memasak Yuigahama memang payah. Ini bukan tentang masalah mampu atau tidaknya – untuk kemampuan dasar saja ia tak punya. Sikap plinplannya di luar kewajaran, bahkan untuk melakukan hal yang mudah saja, ia gagal. Ia adalah orang yang tak ingin kujadikan partner saat tugas di laboratorium. Yang ada, ia cukup plinplan untuk membuat dirinya sendiri terbunuh.
Akhirnya benda itu pun selesai dipanggang, dan keluarlah kue panas yang terlihat gosong. Dari baunya saja bisa kutebak kalau rasanya pahit.
"Ko-kok bisa?" Yuigahama terpaku ngeri saat melihat sebuah aib di hadapannya.
"Aku sungguh tak mengerti... bagaimana mungkin ada kesalahan yang bisa terjadi secara berturut-turut...?" Gumam Yukinoshita. Kurasa ia berkata pelan begitu agar tak didengar Yuigahama. Meski begitu, ia tadi terlihat keceplosan karena geregetan.
Yuigahama mengambil aib itu dan meletakkannya di atas piring. "Mungkin kelihatannya saja begini, tapi... mana kita tahu sebelum mencicipinya!"
"Kau benar. Di sini kita punya orang yang bertugas untuk itu."
Aku tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Yukinoshita. Benda aneh ini kausuruh aku... kalau yang begini, namanya pengujian racun."
"Kok racun, sih?! ...racun ...ya, mungkin saja ini memang beracun?" Dibandingkan sangkalan yang dipaksakannya di awal, Yuigahama kini malah tampak cemas sambil memiringkan kepalanya, seakan ingin bertanya, Bagaimana ini?
Hal tersebut sudah tak perlu dijawab lagi. Kupalingkan wajahku dari ekspresi Yuigahama yang seperti anak anjing itu dan coba menarik perhatian Yukinoshita.
"Hei, apa ini benar-benar harus kumakan? Ini sangat mirip dengan batu arang yang dijual di Joyful Honda."
"Karena kami tak memakai bahan-bahan yang tak layak konsumsi, mestinya kau akan baik-baik saja. Setidaknya begitu. Dan..." Yukinoshita terhenti sejenak, lalu mulai berbisik. "...aku juga akan memakannya, jadi kau tak perlu risau."
"Serius? Jangan-jangan kau ini memang orang baik, ya? Atau jangan-jangan kau memang suka padaku?"
"...setelah kupikir lagi, lebih baik kau makan semuanya dan mati sendiri saja sana."
"Maaf. Tadi aku sempat kaget, makanya aku jadi mengoceh tak jelas." Semua gara-gara kue kering ini... meski patut dipertanyakan, apakah aib yang ada di hadapan kami ini masih bisa disebut kue kering.
"Aku memintamu untuk mencicipinya, bukan justru mempersoalkannya. Terlebih, aku sudah terlanjur menyetujui permintaan Yuigahama. Setidaknya aku harus bertanggung jawab." Yukinoshita menarik piring itu ke sisinya. "Jika tak bisa menemukan akar permasalahannya, situasi seperti ini takkan berakhir. Walau itu tak bisa dianggap sebagai harga yang dibutuhkan untuk sebuah rasa ingin tahu."
Yukinoshita memandangku setelah mengambil satu dari aib berwarna hitam itu – yang mungkin akan salah dikira batu bara. Matanya tampak sedikit berkaca-kaca. "Kita takkan mati, 'kan?"
"Justru itu yang mau kutanyakan..." Kupandangi Yuigahama, yang juga sedang memandang kami, yang seolah juga ingin ikut bergabung.
...bagus. Alangkah baiknya jika ia saja yang memakan semuanya. Ia pun harus mengerti penderitaan orang lain.