=========================================================
Tiba di terjemahan awal... Di sinilah awal mulanya Hachiman dihadapkan ke kenyataan kalau dia harus masuk ke sebuah klub (semacam takdir mungkin), sebenarnya, Bu Hiratsuka sendiri orang yang baik, dia bermaksud ingin menyelamatkan Hachiman dari sikap penyendirinya (yang mungkin akan berdampak buruk di kehidupannya kelak)...
Oiya, alasan kenapa 奉仕部 (Houshi-bu) ane terjemahkan menjadi Klub Layanan Sosial, akan ane jelaskan di beberapa bagian berikutnya...
Selamat Menikmati..
=========================================================
Prolog
__________________________________________________________
"Menengok Kembali Masa-Masa di SMA"
Karya Hachiman Hikigaya, Kelas 2-F
__________________________________________________________
Masa remaja tak lain hanyalah sebuah kebohongan — sesuatu yang jahat.
Mereka yang terpersona olehnya senantiasa tertipu oleh diri mereka sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Mereka membenamkan diri mereka ke dalam keramaian, lalu berkubang dalam pengakuan orang lain. Bahkan parahnya sebuah kegagalan atau hal semacamnya, justru dianggap sebagai salah satu penanda dari masa remaja — yang seluruhnya membekas ke dalam lembar kenangan masing-masing dari mereka.
Salah satu dari sekian contoh.
Kegiatan yang terkait dengan masa remaja, sebut saja, tindak kriminal seperti mengutil ataupun kerusuhan yang bersifat massal, hanya akan dicap sebagai kenakalan remaja.
Kegagalan yang mereka alami saat ujian sekolah, hanya akan disangkal dengan ucapan, "Sekolah tak lebih dari sekadar tempat untuk belajar".
Dengan mengatasnamakan masa remaja, mereka mampu memutarbalikkan segala bentuk norma atau hal yang sudah berlaku di masyarakat. Bagi mereka, berbagai kebohongan, rahasia, kejahatan, bahkan kegagalan sekalipun, mereka anggap sebagai bumbu penyedap dari masa remaja. Segala kecacatan maupun keburukan dari perbuatan tersebut, mereka cap sebagai pengecualian semata. Sedangkan, kumpulan dari setiap kegagalan itu mereka anggap sebagai bagian dari indahnya masa remaja. Dan mereka mencap segala yang bukan hasil dari masa remaja tersebut, tak lain sebagai kegagalan itu sendiri.
Kegagalan yang menjadi penanda dari masa remaja itu, bukankah bisa dianggap pula sebagai esensi masa remaja bagi mereka yang tak bisa berteman? Kesemuanya itu penuh dengan standar ganda.
Oleh karenanya, hal tersebut hanyalah omong kosong. Sebuah kebohongan, dusta, hal yang ditutup-tutupi, serta kecurangan yang pantas untuk dikutuk.
MEREKA sesuatu yang jahat.
Oleh karenanya, tersembunyi keadilan sejati, yang sifatnya paradoks, bagi mereka yang menghindari masa remaja.
Kesimpulan yang bisa kutarik:
RIAJUU, MELEDAK SAJA KAU SANA!
__________________________________________________________
Bab 1 - Biar Bagaimanapun, Hachiman Hikigaya Memang Busuk
Bagian 1
Bagian 1
Sambil mengernyitkan alis matanya, Bu Shizuka Hiratsuka selaku guru Bahasa Jepang di kelasku, membacakan dengan nyaring esaiku itu tepat di depanku. Saat mendengarkannya, kusadari bahwa keahlian menulisku masih jauh dari yang diharapkan. Tadinya kupikir, aku bakal terdengar intelek jika merangkai kata-kata berbobot di dalamnya, namun yang ada, itu malah seperti cara murahan yang biasanya dipakai para penulis di awal kariernya.
Jadi ..., itukah yang membuatku dipanggil ke ruang guru? Sepertinya bukan. Aku juga sadar kalau itu adalah esai amatiran.
Selesai membaca, Bu Hiratsuka menempelkan tangan ke dahinya lalu menghela napas panjang.
"Katakan, Hikigaya. Kau ingat tema untuk esai yang Ibu suruh kerjakan ini?"
"... ingat. Temanya Menengok Kembali Masa-Masa di SMA."
"Sudah jelas, 'kan? Lalu kenapa esai ini malah seperti surat ancaman? Memangnya kau ini teroris? Atau cuma orang bodoh, hah?"
Bu Hiratsuka lalu menggaruk kepalanya sambil mendesah.
Kini aku jadi berpikir, memakai kata Ibu untuk panggilan Ibu Guru kedengarannya lebih menambah daya tarik seksual ketimbang sekadar Guru Perempuan saja.
Aku menyengir selagi melamunkannya, hingga gulungan kertas menghantam kepalaku.
"Perhatikan kalau Ibu bicara!"
"I-iya."
"Tatapanmu kosong, persis seperti ikan mati."
"Berarti tubuh saya kaya omega-3 dong, Bu? Berarti saya genius banget."
Bu Hiratsuka hanya terbengong mendengarnya.
"Hikigaya, esai murahan apa ini? Beri Ibu penjelasan."
Tatapan tajamnya mengarah padaku, dan pandangan geramnya cukup memberi kesan mematikan. Hanya wanita yang dikutuk oleh kecantikan saja yang mampu menampakkan ekspresi seberbahaya itu, hingga tanpa sadar memaksa dan membuat tertekan siapa saja yang melihatnya. Bisa dibilang, itu benar-benar mengerikan.
"Eng ... bagaimana, ya .... Saya memang sudah merenungi kehidupan SMA saya, 'kan? Memang seperti itulah kehidupan SMA zaman sekarang! Esai yang saya tulis sedikit banyak sudah menyinggung hal tersebut," jawabku sambil terbata-bata. Aku bisa gugup hanya karena bicara dengan orang lain, tapi aku lebih gugup lagi jika lawan bicaraku seorang perempuan yang lebih tua.
"Biasanya, tugas semacam ini butuh perenungan atas pengalaman pribadimu, tapi kenapa justru begini?"
"Kalau begitu, harusnya Bu Hiratsuka menyisipkan maksud Ibu itu di kata pengantar, dong. Jika seperti itu, pasti akan saya kerjakan betul-betul. Berarti ini salah Ibu yang sudah memberi tugas menyesatkan, ya 'kan?"
"Hei, Nak. Jangan berlagak pintar di depan Ibu, ya."
"Nak? ... yah, memang benar, sih, beda umur antara saya dengan Bu Hiratsuka memang jauh, jadi, tak masalah jika Ibu memanggil Nak."
"Wuuuss!*
Yang barusan ternyata sebuah tinju. Tinju yang begitu saja dilesatkan secara tiba-tiba. Lebih penting lagi, sebuah keajaiban, karena tinju itu hanya menyerempet di samping pipiku.
"Berikutnya tak akan meleset." Tatapannya penuh keseriusan.
"Ma-maaf, Bu. Saya kerjakan lagi, deh." Aku harus bijak dalam berkata-kata jika ingin menunjukkan rasa sesalku. Dilihat dari keadaannya, Bu Hiratsuka ternyata orang yang sulit untuk merasa puas. Tampaknya tak ada lagi cara selain berlutut dan membungkuk di hadapannya.
Kucoba untuk menyapu lipatan celanaku, dan selagi merapikannya, kutekuk kaki kananku hingga menempel ke lantai, pergerakan yang mulus dan sempurna.
"Asal kau tahu, ini bukan berarti Ibu marah." ... oh, ternyata begitu jawabnya. Terkadang, orang-orang selalu berkata, Aku enggak marah, kok. Jadi bicara saja. Padahal, mereka tetap saja merasa marah. Tapi tak disangka, beliau memang tak benar-benar marah. Yah, terkecuali waktu kusinggung umurnya tadi.
Diam-diam kuamati reaksi beliau sembari mengangkat lutut kananku dari lantai.
Bu Hiratsuka merogoh kantung bajunya yang tampak menonjol karena payudaranya, lalu mengambil sebungkus Seven Stars dari dalamnya dan mengetuk-ngetuk filter-nya ke atas meja — kelakuan orang-orang yang sudah berumur. Setelah mengambil rokok sebatang, beliau nyalakan pemantik seratus yen lalu membakar rokoknya, kemudian menghisapnya sambil memandangku dengan wajah yang serius.
"Kau masih belum bergabung pada klub mana pun, 'kan?"
"Ya, belum."
"... oh, ya, apa kau punya teman?"
Seakan-akan beliau sudah tahu kalau aku memang tak punya teman.
"Se-sepertinya Ibu harus tahu kalau saya menganut azas ketakberpihakan, oleh karenanya, saya tak boleh memiliki hubungan dekat dengan orang lain!"
"Singkatnya, kau tak punya teman, 'kan?"
"Ya-yah, begitu, deh ...."
Mendengar jawabanku, wajah Bu Hiratsuka pun berubah sumringah.
"Jadi memang benar tidak punya, ya? Tepat seperti dugaan Ibu. Hanya dari tatapan kosongmu saja sudah ketahuan, kok!"
Kalau sudah tahu, ya tak usah sampai tanya-tanya seperti tadi, 'kan?
Sambil mengangguk karena sudah mengerti, beliau memandang wajahku dengan ekspresi yang ditahan.
"... lalu, kalau pacar atau semacamnya? Sudah punya, belum?"
Semacamnya? Apa maksudnya itu? Kira-kira apa tanggapan beliau jika kubilang kalau pacarku itu seorang lelaki?
"Sekarang, masih belum."
Karena itu kutegaskan kata sekarang, dengan mempertimbangkan segala harapan yang kelak terjadi di masa mendatang.
"Kasihan, jadi begitu, ya ...."
Sambil menjauhkan pandangannya, mata beliau pun tampak berkaca-kaca. Kuyakin itu hanya karena asap rokok. Sudahlah, hentikan. Berhenti memandangku dengan tatapan sentimentil itu.
Lagi pula, untuk apa beliau mempertanyakan hal barusan? Apa beliau memang seorang guru yang begitu peduli pada muridnya?
Apa beliau ingin menyampaikan padaku jika suatu saat aku bisa menjadi nila setitik, yang bisa merusak susu sebelanga?
Atau mungkin beliau pernah bermasalah sewaktu masih menjadi murid SMA, lalu kembali ke sekolah lamanya ini sebagai seorang guru? Bisa, tidak, kita kembali dulu ke pokok permasalahan?
Jadi ..., itukah yang membuatku dipanggil ke ruang guru? Sepertinya bukan. Aku juga sadar kalau itu adalah esai amatiran.
Selesai membaca, Bu Hiratsuka menempelkan tangan ke dahinya lalu menghela napas panjang.
"Katakan, Hikigaya. Kau ingat tema untuk esai yang Ibu suruh kerjakan ini?"
"... ingat. Temanya Menengok Kembali Masa-Masa di SMA."
"Sudah jelas, 'kan? Lalu kenapa esai ini malah seperti surat ancaman? Memangnya kau ini teroris? Atau cuma orang bodoh, hah?"
Bu Hiratsuka lalu menggaruk kepalanya sambil mendesah.
Kini aku jadi berpikir, memakai kata Ibu untuk panggilan Ibu Guru kedengarannya lebih menambah daya tarik seksual ketimbang sekadar Guru Perempuan saja.
Aku menyengir selagi melamunkannya, hingga gulungan kertas menghantam kepalaku.
"Perhatikan kalau Ibu bicara!"
"I-iya."
"Tatapanmu kosong, persis seperti ikan mati."
"Berarti tubuh saya kaya omega-3 dong, Bu? Berarti saya genius banget."
Bu Hiratsuka hanya terbengong mendengarnya.
"Hikigaya, esai murahan apa ini? Beri Ibu penjelasan."
Tatapan tajamnya mengarah padaku, dan pandangan geramnya cukup memberi kesan mematikan. Hanya wanita yang dikutuk oleh kecantikan saja yang mampu menampakkan ekspresi seberbahaya itu, hingga tanpa sadar memaksa dan membuat tertekan siapa saja yang melihatnya. Bisa dibilang, itu benar-benar mengerikan.
"Eng ... bagaimana, ya .... Saya memang sudah merenungi kehidupan SMA saya, 'kan? Memang seperti itulah kehidupan SMA zaman sekarang! Esai yang saya tulis sedikit banyak sudah menyinggung hal tersebut," jawabku sambil terbata-bata. Aku bisa gugup hanya karena bicara dengan orang lain, tapi aku lebih gugup lagi jika lawan bicaraku seorang perempuan yang lebih tua.
"Biasanya, tugas semacam ini butuh perenungan atas pengalaman pribadimu, tapi kenapa justru begini?"
"Kalau begitu, harusnya Bu Hiratsuka menyisipkan maksud Ibu itu di kata pengantar, dong. Jika seperti itu, pasti akan saya kerjakan betul-betul. Berarti ini salah Ibu yang sudah memberi tugas menyesatkan, ya 'kan?"
"Hei, Nak. Jangan berlagak pintar di depan Ibu, ya."
"Nak? ... yah, memang benar, sih, beda umur antara saya dengan Bu Hiratsuka memang jauh, jadi, tak masalah jika Ibu memanggil Nak."
"Wuuuss!*
Yang barusan ternyata sebuah tinju. Tinju yang begitu saja dilesatkan secara tiba-tiba. Lebih penting lagi, sebuah keajaiban, karena tinju itu hanya menyerempet di samping pipiku.
"Berikutnya tak akan meleset." Tatapannya penuh keseriusan.
"Ma-maaf, Bu. Saya kerjakan lagi, deh." Aku harus bijak dalam berkata-kata jika ingin menunjukkan rasa sesalku. Dilihat dari keadaannya, Bu Hiratsuka ternyata orang yang sulit untuk merasa puas. Tampaknya tak ada lagi cara selain berlutut dan membungkuk di hadapannya.
Kucoba untuk menyapu lipatan celanaku, dan selagi merapikannya, kutekuk kaki kananku hingga menempel ke lantai, pergerakan yang mulus dan sempurna.
"Asal kau tahu, ini bukan berarti Ibu marah." ... oh, ternyata begitu jawabnya. Terkadang, orang-orang selalu berkata, Aku enggak marah, kok. Jadi bicara saja. Padahal, mereka tetap saja merasa marah. Tapi tak disangka, beliau memang tak benar-benar marah. Yah, terkecuali waktu kusinggung umurnya tadi.
Diam-diam kuamati reaksi beliau sembari mengangkat lutut kananku dari lantai.
Bu Hiratsuka merogoh kantung bajunya yang tampak menonjol karena payudaranya, lalu mengambil sebungkus Seven Stars dari dalamnya dan mengetuk-ngetuk filter-nya ke atas meja — kelakuan orang-orang yang sudah berumur. Setelah mengambil rokok sebatang, beliau nyalakan pemantik seratus yen lalu membakar rokoknya, kemudian menghisapnya sambil memandangku dengan wajah yang serius.
"Kau masih belum bergabung pada klub mana pun, 'kan?"
"Ya, belum."
"... oh, ya, apa kau punya teman?"
Seakan-akan beliau sudah tahu kalau aku memang tak punya teman.
"Se-sepertinya Ibu harus tahu kalau saya menganut azas ketakberpihakan, oleh karenanya, saya tak boleh memiliki hubungan dekat dengan orang lain!"
"Singkatnya, kau tak punya teman, 'kan?"
"Ya-yah, begitu, deh ...."
Mendengar jawabanku, wajah Bu Hiratsuka pun berubah sumringah.
"Jadi memang benar tidak punya, ya? Tepat seperti dugaan Ibu. Hanya dari tatapan kosongmu saja sudah ketahuan, kok!"
Kalau sudah tahu, ya tak usah sampai tanya-tanya seperti tadi, 'kan?
Sambil mengangguk karena sudah mengerti, beliau memandang wajahku dengan ekspresi yang ditahan.
"... lalu, kalau pacar atau semacamnya? Sudah punya, belum?"
Semacamnya? Apa maksudnya itu? Kira-kira apa tanggapan beliau jika kubilang kalau pacarku itu seorang lelaki?
"Sekarang, masih belum."
Karena itu kutegaskan kata sekarang, dengan mempertimbangkan segala harapan yang kelak terjadi di masa mendatang.
"Kasihan, jadi begitu, ya ...."
Sambil menjauhkan pandangannya, mata beliau pun tampak berkaca-kaca. Kuyakin itu hanya karena asap rokok. Sudahlah, hentikan. Berhenti memandangku dengan tatapan sentimentil itu.
Lagi pula, untuk apa beliau mempertanyakan hal barusan? Apa beliau memang seorang guru yang begitu peduli pada muridnya?
Apa beliau ingin menyampaikan padaku jika suatu saat aku bisa menjadi nila setitik, yang bisa merusak susu sebelanga?
Atau mungkin beliau pernah bermasalah sewaktu masih menjadi murid SMA, lalu kembali ke sekolah lamanya ini sebagai seorang guru? Bisa, tidak, kita kembali dulu ke pokok permasalahan?
"Ya sudah, kalau begitu, kerjakan lagi saja esaimu."
"Baik."
Dan memang akan kukerjakan.
Aku paham sekarang. Kali ini tulisanku pasti sesuai dengan yang diharapkan; aku harus menulisnya tanpa menyinggung pihak mana pun. Yang isinya tak beda jauh dengan ocehan yang ada di blog para model vulgar maupun aktris pengisi suara semacamnya, contoh:
Makan malam kali ini apa, ya ...? Ya ampun! Ternyata kari!
Begitulah. Tunggu, lalu untuk apa ada pernyataan, Ya ampun! tadi? Jika hanya untuk menandakan ekspresi terkejut, jelas tak ada gunanya.
Sampai di titik ini, segalanya sudah kuperhitungkan. Namun yang terjadi setelah ini, justru lebih dari yang kubayangkan.
"Biar bagaimanapun, ucapan kasar dan sikapmu barusan sudah menyakiti perasaan Ibu. Apa tak ada yang mengajarimu kalau tak boleh membahas masalah umur di depan wanita? Karena sikapmu tadi, jadi Ibu memaksamu untuk bergabung ke Klub Layanan Sosial. Lagi pula, yang namanya salah juga harus dihukum, 'kan?"
Untuk seseorang yang telah dilukai perasaannya, Bu Hiratsuka tak tampak seperti orang yang berwibawa layaknya seorang guru. Kenyataannya, beliau justru lebih ceria dari biasanya, bahkan cara bicaranya pun dibuat lebih menggoda dan menggairahkan.
Itulah yang kupikirkan sekarang. Kata menggairahkan biasanya membuat kita berpikir ke arah yang tak jauh-jauh dari payudara, 'kan? Kenyataannya, mataku sekarang malah tertuju ke arah blus yang menonjolkan payudara Bu Hiratsuka.
Itu memang hal yang tak bisa dibenarkan .... Meski begitu, bisa-bisanya ada orang yang begitu senangnya saat memberi hukuman?
"Klub Layanan Sosial? ... memangnya Ibu mau suruh apa saya di sana?"
Selidik demi selidik. Yang kutahu, kegiatan itu mungkin saja hal-hal semacam membersihkan selokan, atau yang terburuk, menculik orang. Amit-amit jabang bayi, deh.
"Ikuti saja Ibu."
Bu Hiratsuka lalu mematikan rokoknya ke asbak dan segera bangkit dari tempat duduknya. Aku masih diam tak bergerak, memikirkan tentang pengajuan yang tanpa penjelasan maupun pengenalan itu, namun rupanya, Bu Hiratsuka sudah ada di depan pintu seraya menoleh ke hadapanku.
"Ayo jalan!"
Disertai alis yang berkerut dan kebingungan di wajahku ini, kuikuti beliau dari belakang.
Lanjut
"Baik."
Dan memang akan kukerjakan.
Aku paham sekarang. Kali ini tulisanku pasti sesuai dengan yang diharapkan; aku harus menulisnya tanpa menyinggung pihak mana pun. Yang isinya tak beda jauh dengan ocehan yang ada di blog para model vulgar maupun aktris pengisi suara semacamnya, contoh:
Makan malam kali ini apa, ya ...? Ya ampun! Ternyata kari!
Begitulah. Tunggu, lalu untuk apa ada pernyataan, Ya ampun! tadi? Jika hanya untuk menandakan ekspresi terkejut, jelas tak ada gunanya.
Sampai di titik ini, segalanya sudah kuperhitungkan. Namun yang terjadi setelah ini, justru lebih dari yang kubayangkan.
"Biar bagaimanapun, ucapan kasar dan sikapmu barusan sudah menyakiti perasaan Ibu. Apa tak ada yang mengajarimu kalau tak boleh membahas masalah umur di depan wanita? Karena sikapmu tadi, jadi Ibu memaksamu untuk bergabung ke Klub Layanan Sosial. Lagi pula, yang namanya salah juga harus dihukum, 'kan?"
Untuk seseorang yang telah dilukai perasaannya, Bu Hiratsuka tak tampak seperti orang yang berwibawa layaknya seorang guru. Kenyataannya, beliau justru lebih ceria dari biasanya, bahkan cara bicaranya pun dibuat lebih menggoda dan menggairahkan.
Itulah yang kupikirkan sekarang. Kata menggairahkan biasanya membuat kita berpikir ke arah yang tak jauh-jauh dari payudara, 'kan? Kenyataannya, mataku sekarang malah tertuju ke arah blus yang menonjolkan payudara Bu Hiratsuka.
Itu memang hal yang tak bisa dibenarkan .... Meski begitu, bisa-bisanya ada orang yang begitu senangnya saat memberi hukuman?
"Klub Layanan Sosial? ... memangnya Ibu mau suruh apa saya di sana?"
Selidik demi selidik. Yang kutahu, kegiatan itu mungkin saja hal-hal semacam membersihkan selokan, atau yang terburuk, menculik orang. Amit-amit jabang bayi, deh.
"Ikuti saja Ibu."
Bu Hiratsuka lalu mematikan rokoknya ke asbak dan segera bangkit dari tempat duduknya. Aku masih diam tak bergerak, memikirkan tentang pengajuan yang tanpa penjelasan maupun pengenalan itu, namun rupanya, Bu Hiratsuka sudah ada di depan pintu seraya menoleh ke hadapanku.
"Ayo jalan!"
Disertai alis yang berkerut dan kebingungan di wajahku ini, kuikuti beliau dari belakang.
Lanjut








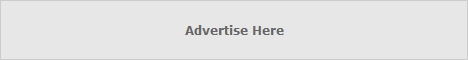



0 komentar:
Posting Komentar